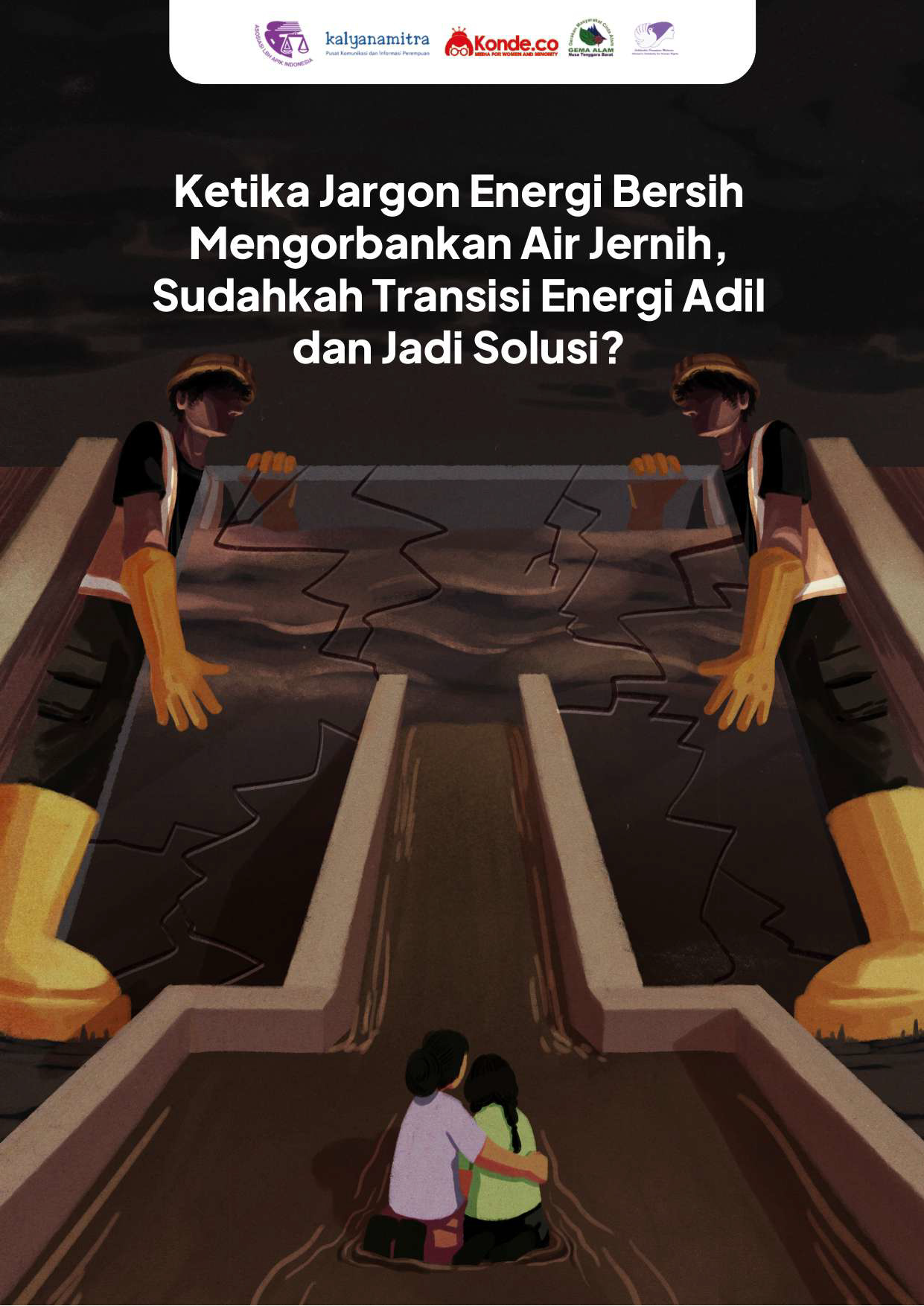Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKHP) yang telah lama digodok oleh Pemerintah digadang-gadang oleh beberapa pihak untuk segera disahkan tahun ini. Sayangnya, proses panjang dalam penyusunan RUU tersebut dianggap belum cukup menyempurnakan isi muatannya, salah satunya dikarenakan aspek pluralitas belum cukup kentara. Rancangan tersebut dianggap belum mampu mengakomodir kepentingan dan partisipasi kelompok rentan.
Melihat polemik tersebut, Khotimun Sutanti menyuguhkan analisa dan catatan singkat mengenai pasal-pasal RKUHP dari sudut pandang perempuan dan kelompok rentan yang tidak hanya bersumber dari LBH Apik tetapi juga merupakan kompilasi dari perspektif penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Dalam diskusi oleh ICJR pada Kamis (06/05), perempuan yang akrab disapa Imun tersebut memberikan beberapa catatannya dengan menilik draf terakhir RKUHP.
Catatan yang pertama, berkaitan dengan konsep living law atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia dan Pancasila pun menjadi standarnya. Konsep living law sendiri tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 597 Buku I RUKHP. Sayangnya, konsep tersebut dianggap menjadi kabur dan multitafsir karena pada setiap elemen masyarakat bahkan daerah memiliki ukuran yang tidak seragam. Contohnya adalah dimensi dalam memandang kekerasan seksual sendiri yang tidaklah sama.
“Jika yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat yang mana tidak hanya hukum adat saja, sifatnya adalah dinamis sehingga cukup membingungkan. Untuk mengukurnya, penegakan, dan pengawasannya akan menyulitkan” ucap perwakilan Asosiasi LBH Apik tersebut.
Selain itu, dampak dari pasal tersebut juga dinilai akan melahirkan peraturan-peraturan daerah yang sifatnya diskriminatif yang akan menyasar pada perempuan dan kelompok rentan. Khotimun memberikan konklusi bahwa sebaiknya pasal terkait dihapuskan saja dari draf RKUHP.
Khotimun juga menyoroti mengenai kategorisasi perkosaan sebagai kejahatan tubuh. Sebelumnya, telah ada kemajuan dalam delik perkosaan di KUHP yang diatur pada Bab Kesusilaan. Dalam draf RKUHP, hal tersebut diubah dengan dimasukan pada Bab Tindak Pidana Terhadap Tubuh. Namun, ia menilai bahwa perkosaan tidak hanya memberikan dampak pada tubuh tetapi juga integritas atau jiwa korban.
Dari hal tersebut ia melempar pertanyaan yang diharapkan mampu menjadi bahan diskursus lebih lanjut, “Apakah mungkin perkosaan ini lebih tepat masuk dalam tindak pidana terhadap orang?”
Kemajuan lain dapat dilihat dalam Pasal 479 RKUHP yang telah memperluas unsur perkosaan dengan mengakomodasi marital rape yang kemudian melahirkan konsekuensi bahwa perkosaan tidak hanya terjadi di luar perkawinan tetapi juga di dalam ikatan tersebut. Pasal ini memberikan penegasan terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
Selain itu, juga telah ada kemajuan konsep dari segi perbuatan dengan unsur perkosaan, yaitu tidak lagi dibatasi dengan ‘masuknya bagian tubuh atau benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya’. Kendati demikian, menurut Khotimun masih ada catatan hitam bahwa RUU tersebut belum mengakomodir pengalaman korban yang lain, khususnya dalam hal relasi kuasa, bujuk rayu, serta tipu daya.
“Banyak korban perkosaan karena relasi kuasa, bujuk rayu, serta tipu daya kemudian dianggap bukan perkosaan. Kalau dimasukan dalam pencabulan maka tentu hukumannya akan lebih ringan. Parahnya lagi kalau itu tidak diklaim sebagai tindak pidana bahkan dinilai sebagai tindakan suka sama suka, tentu akan menjadi persoalan” tegas Khotimun.
Khotimun juga menambahkan catatan dalam ketentuan perkosaan mengenai frasa ‘perbuatan yang tidak dikehendaki oleh korban’ yang sebelumnya termaktub dalam draf tahun 2015 sampai 2016 kemudian hilang pada draf 24 September 2019. Frasa tersebut menurutnya justru sangat krusial. Frasa ‘tidak dikehendaki’ tersebut tidak lantas ditafsirkan antara penolakan atau persetujuan, tetapi harus juga didalami situasi-situasi lain di belakang peristiwa perkosaan tersebut. Faktanya, sebagian besar perempuan yang menjadi korban perkosaan menyatakan ketidaksetujuannya melalui psikis. Ia menilai bahwa frasa tersebut seharusnya tetap masuk dalam draf terbaru RKUHP.
Hal lain yang juga masih menjadi ‘PR’ bagi RKUHP adalah mengenai pengaturan tentang persetubuhan terhadap perempuan dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya. Sampai pada draf terakhir, masih belum ada penafsiran yang jelas mengenai istilah ‘pingsan dan tidak berdaya’ sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.
“Frasa tidak berdaya itu selama ini cukup sulit ditafsirkan, apakah itu karena mabuk kemudian dianggap pingsan dan tidak berdaya? Atau seperti apa? Kita perlu menafsirkan yang lebih detail lagi,” pungkas Khotimun.
Catatan lain yang tidak kalah penting adalah terkait adanya kriminalisasi dalam upaya penunjukan alat pencegahan kehamilan yang diatur di dalam Pasal 414 sampai dengan 416 RKUHP. Pasal tersebut pada intinya melarang seseorang untuk mempertunjukkan secara terang-terangan dengan atau tanpa diminta, atau memberikan informasi untuk memperoleh alat kontrasepsi. Hal tersebut tentu kontradiktif dengan program Pemerintah dalam memerangi angka kasus HIV serta melemahkan upaya untuk mendorong dan mewujudkan masyarakat yang sehat.
Selain itu, terhadap isu aborsi juga turut menjadi poin yang perlu dievaluasi. RKUHP sendiri dianggap mundur dibandingkan Undang-Undang Kesehatan dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 yang telah mengakomodir aborsi terhadap korban perkosaan. Meskipun demikian, hanya dokter yang dapat menjadi pihak yang dikecualikan dalam melakukan tindakan pengguguran.
Tentu perlu dijelaskan pula bagaimana posisi korban dan para medis lainnya apabila dalam kondisi darurat medis ataupun karena perkosaan kemudian melakukan tindakan aborsi. Khotimun memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan ketentuan dalam RKUHP dengan UU Kesehatan dengan juga turut melakukan evaluasi terhadap batas usia pengguguran kandungan.
Selain itu, dari kacamata kelompok penyandang disabilitas terdapat beberapa catatan untuk RKUHP. Salah satunya seperti penggunaan kata ‘menderita’ bagi penyandang disabilitas yang secara implisit seolah-olah memposisikan disabilitas layaknya penyakit. Persoalan lain adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang memberikan pengecualian terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual dengan spesifikasi kategori derajat tertentu maka perlu diperdalam lebih lanjut seperti apa batasan ringan, sedang, serta yang dimaksud dengan berat. Tidak luput, mekanisme serta wewenang dalam penentuan pengecualiaan tersebut juga perlu diperjelas.
Sumber: mahkamahnews.org – See: https://mahkamahnews.org/2021/05/07/bingkai-kritik-rkuhp-dalam-sudut-pandang-perempuan-dan-kelompok-rentan/