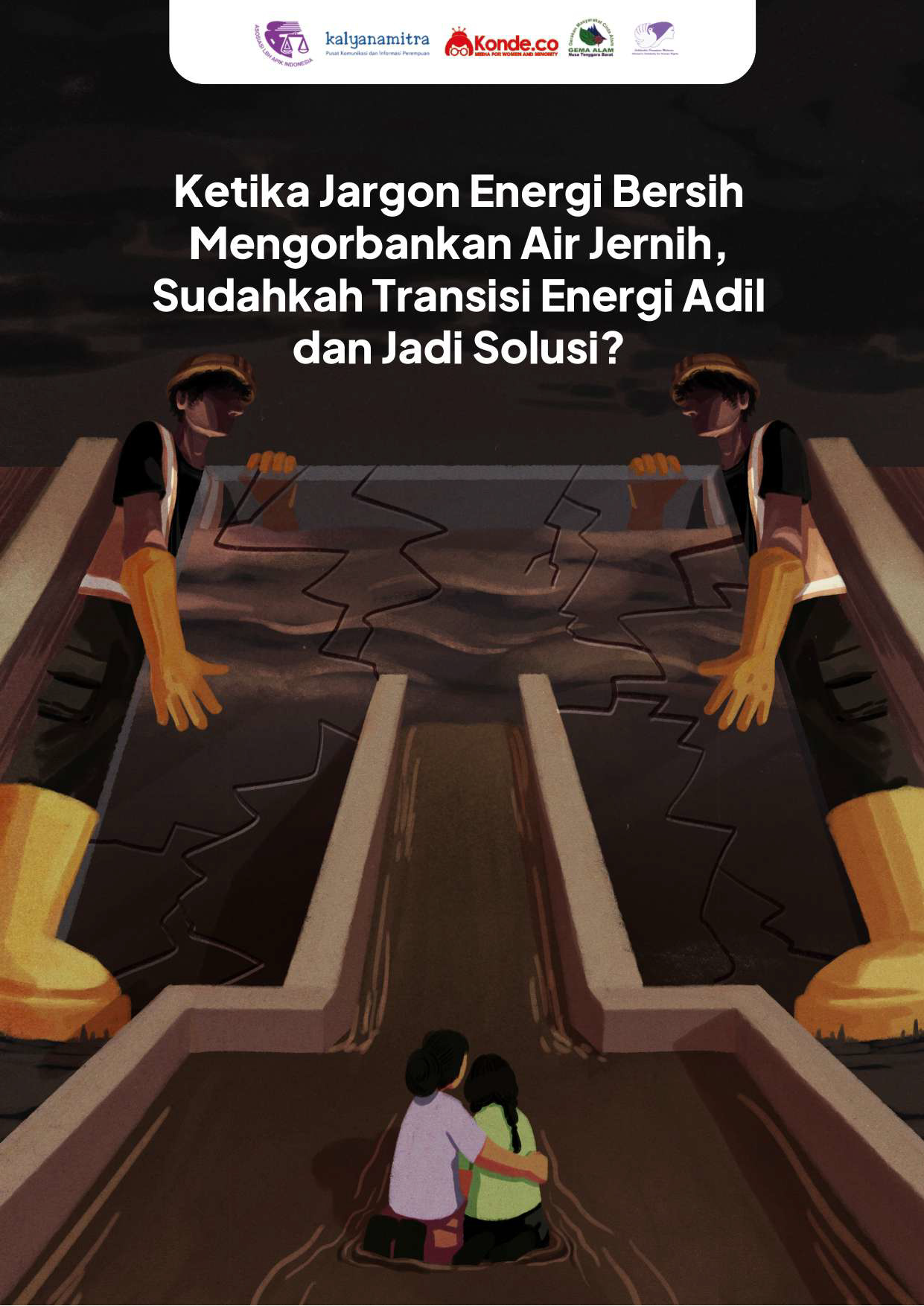Ilustrasi MI
Oleh: Nursyahbani Katjasungkana Ketua Pengurus Asosuasi LBH APIK Indonesia | Opini
TEPAT pada tahun ke-39 pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan), tanggal 24 Juli, kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap seorang pekerja rumah tangga (PRT) bernama SK (Media Indonesia, 22 Desember 2022) diputus.
Kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini banyak memperoleh perhatian masyarakat karena tingkat kekejaman yang dilakukan para terdakwa tidak terbayangkan bisa terjadi.
Seperti sudah diduga, dengan mengacu pada tuntutan jaksa, putusan hakim lebih rendah daripada tuntutan kecuali terhadap salah satu terdakwa yang divonis 4 tahun penjara. Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp275 juta, jumlah yang direkomendasikan oleh LPSK. Di persidangan terdakwa memberikan tambahan Rp200 juta sebagai bentuk bantuan, dan itu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan terdakwa.
Kasus SK sendiri, seperti juga kasus-kasus kekerasan terhadap PRT lainnya, merupakan bentuk nyata dari sebuah perbudakan modern. Pada umumnya, calon-calon PRT direkrut penyalur di desanya, atau PRT datang mencari pekerjaan melalui penyalur. Para pemberi kerja menghubungi penyalur dengan membayar sejumlah uang jasa. Selanjutnya, menandatangani kontrak kerja dengan waktu tertentu, dan dalam waktu tertentu tersebut PRT dilarang mengundurkan diri meski kondisi kerja tidak sesuai dengan yang ada dalam kontrak.
Dalam konteks ini, hubungan PRT dan pemberi kerjanya seperti hubungan jual beli. Tidak mengherankan jika dalam kontrak kerja lebih banyak kewajiban PRT daripada hak-haknya. Dalam kasus SK, misalnya, tidak ada batasan jam kerja dan jenis pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selama bekerja sejak April hingga September 2022, SK tidak pernah menerima upah. Yang jelas, tidak ada sanksi bagi pemberi kerja yang tidak membayar upahnya. Penyalur PRT yang menjadi mediatornya juga tidak membantu. Bahkan kontrak kerjanya pun tidak diberikan kepada SK. Ironisnya, 6 rekan kerjanya yang lain malah membantu pemberi kerja (terdakwa) ikut menyiksanya, tanpa dapat menolaknya. Dari fakta ini, betapa berkuasanya pemberi kerja terhadap PRT-nya, bahkan untuk melakukan kejahatan terhadap rekan sekerjanya sendiri pun, mereka tidak sanggup menolak. Kasus SK adalah contoh nyata sebuah perbudakan modern.
Sangat disayangkan bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini tidak mampu melihat kenyataan ini. Dari hukuman yang dijatuhkan, PN Jakarta Selatan tidak mampu mengabstraksi kasus SK dari asas yang paling mendasar bagi pengadilan: keadilan sosial dan keadilan gender. Padahal Peraturan MA No 3/2017 sudah memberikan pedoman untuk menerapkan asas tersebut. Ketimpangan relasi kuasa antara pemberi kerja dan PRT yang berada di balik kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang terjadi, tampaknya tidak mampu menyentuh nurani para hakim.
Sebetulnya, diskriminasi terhadap SK juga telah terjadi sejak di tingkat kepolisian. Upaya para pendamping dari Jala PRT dan APIK Jakarta, juga kesaksian ayah SK untuk meyakinkan bahwa kasus ini bukan hanya kejahatan KDRT tapi juga kekerasan seksual, ditolak polisi. Pengakuan terdakwa bahwa mereka telah melakukan penyiksaan pada bagian kemaluan SK juga tidak mampu menggugah hakim untuk memperbaiki dakwan jaksa.
Masukan dari Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) yang disampaikan APIK, LBH APIK Semarang dan Medan, LBH Semarang, dan mungkin dari organisasi lainnya untuk membantu membongkar asumsi-asumsi yang ada di balik kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang terjadi dalam kasus SK ini, diabaikan begitu saja. APIK, misalnya, meminta majelis hakim untuk memperbaiki kesalahan awal polisi dan jaksa yang tidak memasukkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Sebetulnya, majelis Hakim secara ex officio dapat melakukan penemuan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Perempuan. Pasal 5 (Penghapusan Pembakuan Peran Gender) dan 14 (Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Perdesaan) Konvensi Perempuan mewajibkan negara termasuk majelis hakim lewat putusannya untuk melakukan tindakan yang tepat, untuk menghapuskan diskriminasi dan melakukan pemberdayaan perempuan miskin perdesaan seperti SK ini.
APIK juga meminta Majelis Hakim PN Jakarta Selatan untuk memperhitungkan hilangnya kesempatan bekerja dan hidup layak karena SK saat ini telah menjadi penyandang disabilitas. Tidak semestinya restitusi yang diberikan kepada SK yang jumlahnya jauh dari kerugian dan penderitaan yang dialami oleh SK sampai seumur hidupnya menjadi pertimbangan untuk mengurangi ancaman hukuman sebagaimana pedoman yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI No 1 Tahun 2021. Dengan ketentuan ini, Kejaksaan Agung seolah menjadikan proses peradilan sebagai pasar tempat jual beli hukuman.
Dari kasus SK ini dan juga ribuan kasus kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang dialami PRT baik di dalam maupun di luar negeri, cukuplah bagi kita untuk tidak mengulur waktu lagi dalam memberikan perlindungan hukum kepada PRT yang jumlahnya semakin bertambah. Survei ILO 2017 menyatakan bahwa jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta orang. Dengan bertambah cepat bertumbuhnya kelas menengah di Indonesia 5 tahun terakhir, Jala PRT memperkirakan jumlah tersebut telah mencapai 10 juta orang.
Kontribusi mereka terhadap keluarga dan pembangunan di desanya sangat signifikan, bahkan pendapatan PRT yang bekerja di Luar negeri menjadi devisa negara yang setiap tahunnya ditarget cukup tinggi. Tidak malukah kita kepada mereka, karena mereka senyatanya telah ikut membantu perekonomian Indonesia, dan bahkan bukan tidak mungkin ikut membayar gaji para pejabat negara kita. Termasuk para hakim, polisi, jaksa, bahkan anggota DPR dan pejabat pemerintah yang lain?
Pengakuan, hak, dan peredistribusian
PHP dalam judul tulisan ini bukan singkatan dari ‘pemberi harapan palsu’ sebagaimana sering digunakan kaum milenial bagi mereka yang sering memberikan harapan palsu dalam hubungan percintaan atau perkawanan, meski memang para PRT selama 19 tahun terakhir ini senantiasa diberikan harapan palsu oleh DPR. Usulan RUU PPRT dari Jala PRT bersama masyarakat sipil lainnya sejak 2004 telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional. Namun, RUU tersebut tidak kunjung menjadi prioritas pembahasan meski pada awalnya, anggota Fraksi PDIP (Dyah ‘Oneng’ Pitaloka) dan PPP (Asyokawati) telah mengadvokasikannya.
Fraksi besar lain waktu itu menolaknya karena menganggap PRT sebagai sektor informal tidak perlu ‘cawe-cawe’ negara. Mereka menganggap bahwa PRT berada dalam lingkungan hukum adat dan budaya Indonesia yang didasarkan pada asas kekeluargaan (sic!). Suatu hubungan kekeluargaan yang manipulatif, mengingat kondisi kerja mereka yang eksploitatif.
Baru pada 2022 Badan Legislasi DPR akhirnya membahas RUU PPRT, dan pada awal tahun ini disahkan oleh Sidang Paripurna DPR sebagai RUU inisiatif DPR. Atas keputusan tersebut, Presiden segera mengeluarkan surat presiden untuk segera membahasnya dan pemerintah pun telah membuat daftar Isian masalah yang telah diserahkan kepada DPR pada 22 Mei yang lalu. Namun, sampai masa sidang ke-3 tahun ini berakhir, dan beberapa RUU telah disahkan, agenda pembahasan RUU PPRT tidak kunjung ada kabar.
Seorang anggota DPR dari Fraksi PKB dalam sebuah seminar baru-baru ini menyatakan bahwa RUU PPRT ini sarat dengan nuansa politik berkaitan dengan cost and benefit electoral yang akan diperoleh partai-partai yang ada di DPR. Terdapat persaingan antarfraksi untuk mendapatkan kredit dari pengesahan RUU ini, mengingat fraksi-fraksi besar justru menolak RUU ini sejak awal pembahasan di Badan Legislasi.
Kenyataan ini sungguh menyedihkan karena nasib sekelompok besar masyarakat perdesaan yang termarginalkan–mayoritas perempuan–yang selama ini belum memperoleh manfaat pembangunan, hanya dijadikan permainan politik sekelompok orang, yang justru telah memperoleh manfaat tidak terhingga atas kehadiran dan kontribusi mereka dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sehingga mereka (para pemberi kerja) itu dapat berkiprah di ranah produktif.
Namun, inti dari konsep PHP yang ingin saya kemukakan dalam tulisan ini ialah berkaitan dengan pengakuan, hak, dan peredistribusian (pendapatan/kekayaan). Konsep PHP atau dalam bahasa Inggris Triple R (recognition, rights and redistribution) diintroduksi oleh Wieringa dan Vargas (1995) guna mengatasi segala bentuk ketimpangan sosial dan gender.
Konsep ini diperlukan pada sekelompok masyarakat dan khususnya perempuan yang sering mengalami diskriminasi dan kekerasan akibat tidak adanya pengakuan, perlindungan hak, dan peredistribusian pendapatan atau kekayaan (negara/elite).
Berbagai kebijakan yang diberikan pemerintah kepada mereka sehingga menguasai sebagian besar sumber daya alam dan ekonomi telah memarginalkan sekelompok besar masyarakat khususnya perempuan. Pendekatan dengan pemberian bansos dan BLT sebenarnya mengasumsikan bahwa rakyat hanya berhak atas remah-remah kue pembangunan, yang sama sekali tidak sustain karena lebih bersifat karitatif ketimbang pemberdayaan.
Data terbaru yang dikemukakan oleh Muhammad Mar’uf SE, Executive Director and Head of CNBC Indonesia Research (Fakta Telanjang Ketimpangan Ekonomi RI, Juli 2023), menunjukkan bahwa pascapandemi, jurang kaya dan miskin makin melebar. Tanpa bansos dan BLT atau PKH maka jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan akan bertambah sebesar 35%.
Data itu juga menyebutkan bahwa upah rata-rata buruh di empat sektor (sejumlah 94,2 juta) hanya sebesar Rp2,4 juta dan kesenjangan upah berdasarkan gender juga cukup besar. Sebaliknya, penikmat industri ekstraktif berpesta pora dengan kekayaan melimpah. Menurut Global Wealth Databook 2017, harta milik empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Menanggapi data ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak berujung pada kesetaraan, bahkan dampaknya semakin berkurang (BBC News Indonesia, 2017).
Sementara itu, PRT karena digolongkan buruh pada sektor informal tidak dihitung kontribusi ekonominya terhadap pembangunan negara. Mereka ada dalam survei, tapi hasilnya tidak menjadi dasar bagi pengakuan pekerjaan dan perbaikan hidup mereka. Hal yang masih melekat kuat karena PRT melakukan pekerjaan yang menjadi domain perempuan dan dianggap alamiah. Karena itu dianggap tidak perlu memperoleh pendidikan dan peningkatan keterampilan. Dan, karena itu, tidak pula memerlukan perlindungan hukum, termasuk tidak perlu memperoleh upah yang layak dan jaminan kesehatan.
Pikiran tidak adil ini sudah seharusnya dibuang jauh-jauh oleh pimpinan dan para anggota DPR yang selama ini menghambat pengesahan RUU PPRT. Hubungan kerja tidak ditentukan oleh lokasi di rumah, atau di pabrik atau di kantor, tetapi ditentukan oleh produk yang dihasilkan–bagi PRT produk utamanya ialah layanan jasa–dan kesepakatan yang dibuat. Pengesahan RUU PPRT menjadi UU adalah bentuk pengakuan atas pekerjaan PRT yang memberikan jasa layanan rumah tangga. Karena itu, hak-hak mereka harus dijamin dan dilindungi.
Penerapan konsep PHP, khususnya terkait peredistribusian, mutlak harus dipahami oleh setiap pembuat kebijakan. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan (negara) adalah sebuah cara untuk melakukan reparasi sosial atas berbagai ketimpangan dan kemiskinan struktural yang terjadi.
Peredistribusian kekayaan dan pendapatan juga harus dilakukan terutama karena saat ini hanya diokupasi oleh sekelompok kecil yang memperoleh privilese atas kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk insentif pajak yang mereka nikmati selama ini. DPR dan pemerintah mempunyai kesempatan untuk melakukan pemberdayaan perempuan perdesaan dengan mengesahkan RUU PPRT.
Pengesahan RUU PPRT mutlak untuk segera dilakukan demi melindungi 10 juta orang PRT yang jumlahnya kian lama kian membesar. Belum terhitung mereka yang bekerja di luar negeri. DPR dan pemerintah, sesuai dengan fungsi dan mandat konstitusionalnya, mempunyai kewajiban untuk melakukan reparasi sosial ekonomi serta afirmasi terhadap kelompok perempuan peedesaan ini, serta menghapus stereotipe dan pembakuan peran gender yang mengakibatkan diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi terhadap mereka.
Konvensi Perempuan juga memandatkan kepada setiap negara yang meratifikasi untuk melaksanakan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan tanpa kecuali. Kebijakan afirmasi, baik yang tercantum dalam Pasal 4 Konvensi Perempuan maupun Pasal 28 H dan 28 I UUD 1945, hendaknya tidak hanya bisa dinikmati sekelompok perempuan elite atau menengah atas, yang dengan modal sosial dan finansialnya dapat meraih pemenuhan hak-hak sosial politik dan ekonominya secara penuh. Kebijakan tersebut juga dibutuhkan oleh seorang yang bernasib seperti SK dan kawan-kawan PRT lainnya.
Sumber: https://mediaindonesia.com/opini/600217/perlindungan-terhadap-prt-dan-php-oleh-dpr